Ketika Pakar Ditiadakan, Informasi Benar Disangkal Dan Kedunguan Dibanggakan
Banyak yang menyebut saat ini merupakan era matinya akhlak. Sebab orang yang tak tahu, atau sekadar tahu mudah sekali membagi-bagikan pendapatnya tersebar secafa massif. Dan bersamaan, dalam situasi yang sama, para pakar ditiadakan, informasi yang benar disangkal, dan kedunguan dibanggakan.
Dan sayangnya lagi, kaum cendekia, dosen, mahasiswa tak sanggup memverifikasi tapi justru sebagian ikut menyebarkan info-info yang tidak benar.
Maka inilah yang kita hadapi.
Kita berada dalam situasi dimana kita sedang menghadapi musuh bersama--yang dalam dokumen human fraternity--disebut ekstremisme akut (fanatic extremism), hasrat saling memusnahkan (destruction), perang (war), intoleransi (intolerance), serta saling benci (hateful attitudes). Dokumen ini merupakan hasil pertemuan dua tokoh agama besar dunia, Paus Fransiskus dengan Imam Besar Al Azhar, Syekh Ahmad elTayyeb, pada 2019 lalu.
Dan lagi-lagi yang disayangkan, masalah fundamental ini tidak banyak dibahas, namun kita justru membenturkan dua tema penting agama dan kebangsaan dalam bingkai politik pragmatis dan perebutan kekuasaan. Bentuk paling vulgar dari benturan tersebut adalah jualan emosi umat dan politisasi agama. Ini masih terus terjadi tidak makin menyurut.
Emosi umat dijual dengan modus agamanya diserang, tokoh agamanya diserang, atau dihadapkan dengan kekalahan umat secara ekonomi dan politik. Hal ini diperparah dengan masifnya informasi yang disebarkan untuk unjuk kekuatan, meskipun informasinya tidak selalu shohih, dan sikap yang terlalu defensif dalam beragama, seperti melarang perdebatan, komentar, atau kritik terhadap agama.
Jika disinformasi dan kekakuan beragama ini dibiarkan, lama-lama kita tidak terbiasa bertabayun, mengklarifikasi setiap informasi yang diterima, melainkan justru gemar memberi ancaman dan caci maki.
Diperlukan usaha kolektif untuk meredam emosi dengan cara meningkatkan literasi dan memberikan teladan akhlak mulia. Kemudian, daripada emosi umat dipermainkan sehingga kita tidak bisa berpikir masalah-masalah fundamental, sebaiknya emosi ini disalurkan menuju hal-hal yang positif, seperti pemberdayaan sosial dan ekonomi.
Selanjutnya, politisasi agama adalah penafsiran teks agama secara serampangan demi kepentingan politik, baik oleh oposisi, maupun pemerintah. Karena hal ini, mimbar keagamaan tidak lagi membahas kebenaran, tetapi pembenaran.
Sejauh ini, masih banyak cendekiawan yang berlepas tangan terhadap masalah-masalah tersebut. Alasannya bermacam-macam, seperti khawatir di-bully, di-hack, atau diancam dibunuh. Mungkin kita perlu belajar dari Afghanistan. Ketika kelompok Taliban berkuasa di sana, kaum cendekia cenderung diam. Ada yang takut, ada yang memang mendiamkan karena menyepelekan. Namun, ketika mereka berkuasa, justru kaum cendekia yang mereka target. Ironis bahwa Taliban yang artinya gerakan pelajar justru menjadi gerakan anti keilmuan. Yang jelas, inilah akibat dari tak acuhnya kaum cendekia.
Sebagai kaum cendekia, paling tidak ada beberapa hal yang perlu dilakukan.
Pertama, berkeyakinan bahwa info yang valid haruslah diberikan pemegang otoritas keilmuan. Dalam bahasa agama, kita perlu mengecek pembawa informasi, apakah dia bersanad atau tidak.
Kedua, memverifikasi setiap informasi, termasuk dari pakar. Dibutuhkan sikap skeptis atau ingin tahu akan kebenaran, bukannya membenarkan apa yang diinginkan.
Ketiga, berprinsip bahwa sebuah informasi yang diverifikasi haruslah berdasarkan data, bukan personal. Apabila informasi hanya dibantah dengan labelling, maka hal tersebut akan mematikan diskusi. Keempat, menyadari bahwa ilmu itu berjenjang. Janganlah tergesa-gesa memperoleh ilmu.
"Jangan minum kopi saat masih panas. (Hendaknya), hirup dulu aromanya, baru diminum pelan-pelan.”
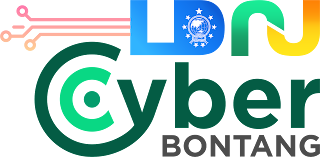

Posting Komentar